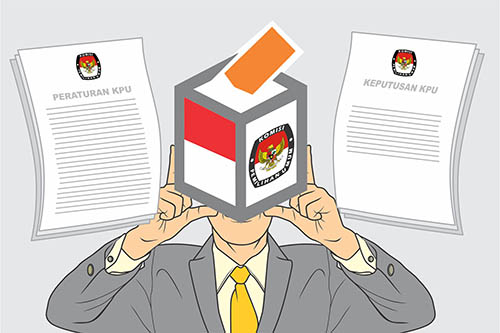INAnews.co.id, Jakarta– Pengamat politik Adi Prayitno mengungkapkan kritik tajam terhadap realitas politik Indonesia yang sarat dengan praktik politik kepalsuan dan pragmatisme transaksional. Dalam sebuah pernyataan yang mengurai kompleksitas demokrasi Tanah Air, Adi menyoroti fenomena calon politisi yang gemar melontarkan gagasan besar saat kampanye, tetapi kemudian gagal mengimplementasikan janji-janji mereka setelah terpilih.
Adi mengakui mimpi politik Indonesia sebagai ruang publik yang penuh gagasan dan ide besar, namun mengingatkan bahwa realitas yang terjadi sangat berbeda. “Satu sisi kita berharap politik diwarnai gagasan, tapi faktanya banyak politisi lupa mewujudkan janji ketika sudah duduk di kursi kekuasaan,” ujarnya lewat akun YouTube-nya, kemarin, Rabu (16/7/2025).
Menanggapi pernyataan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menyebut politik Indonesia sebagai “politik kepalsuan” yang justru disukai publik, Adi semakin mempertegas bahwa politik “gorong-gorong” tanpa gagasan merupakan bentuk nyata dari politik pencitraan. Menurutnya, politik seperti ini tidak menawarkan solusi substantif, melainkan hanyalah upaya mendapatkan simpati masyarakat melalui kehadiran fisik di lapangan dan bantuan sosial, tanpa visi yang jelas.
“Realitas politik kita hari ini adalah pemimpin yang sering turun ke masyarakat, bertemu dari satu gorong-gorong ke gorong-gorong lain, membawa bantuan, lebih mudah menang pemilu daripada yang punya gagasan besar tapi jarang turun,” tegas Adi. Ia menilai pola ini menjadi “jebakan” demokrasi di Indonesia yang harus segera diubah.
Kritik paling mendalam diarahkan pada partai politik yang selama ini menjadi kendaraan utama perebutan kekuasaan dalam sistem politik Indonesia. Menurut Adi, partai politik masih sangat rentan dengan praktik politik transaksional dan pragmatisme, yang mengesampingkan ideologi dan gagasan besar demi pencapaian materi dan kekuasaan.
“Kalau partai politik mau serius, mereka bisa menjadi garda terdepan untuk menghapus politik pragmatis dan transaksional, kemudian membangun politik berbasis gagasan dan ideologi,” katanya. Adi menekankan pentingnya kaderisasi pemimpin yang tidak hanya bermodalkan retorika tebal dan kunjungan simbolis, tetapi juga benar-benar memahami masalah rakyat di “gorong-gorong” yang selama ini diabaikan.
Namun, kondisi saat ini ia nilai masih jauh dari ideal. Perang gaya politik bertumpu pada citra dan distribusi materi dirasa jauh lebih efektif menggaet simpati masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah ke bawah yang selama ini menjadi mayoritas pemilih.
Adi menutup dengan harapan agar di masa depan muncul pemimpin yang “mampu mengawinkan” gagasan besar dengan kehadiran nyata di masyarakat—pemimpin yang tidak hanya piawai berretorika di menara gading, tapi juga paham betul dengan persoalan hidup riil rakyatnya.
Sebagai catatan kritis, pernyataan Adi Prayitno menimbulkan pertanyaan besar tentang kualitas demokrasi Indonesia; apakah politik benar-benar menjadi wahana pemecahan masalah dan perwujudan aspirasi rakyat, atau sekadar arena pencitraan yang sarat kepalsuan dan pragmatisme? Realitas ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi partai politik, elite, dan masyarakat pemilih agar negeri ini bisa meninggalkan era “politik gorong-gorong kosong” menuju politik gagasan yang substansial dan berintegritas.